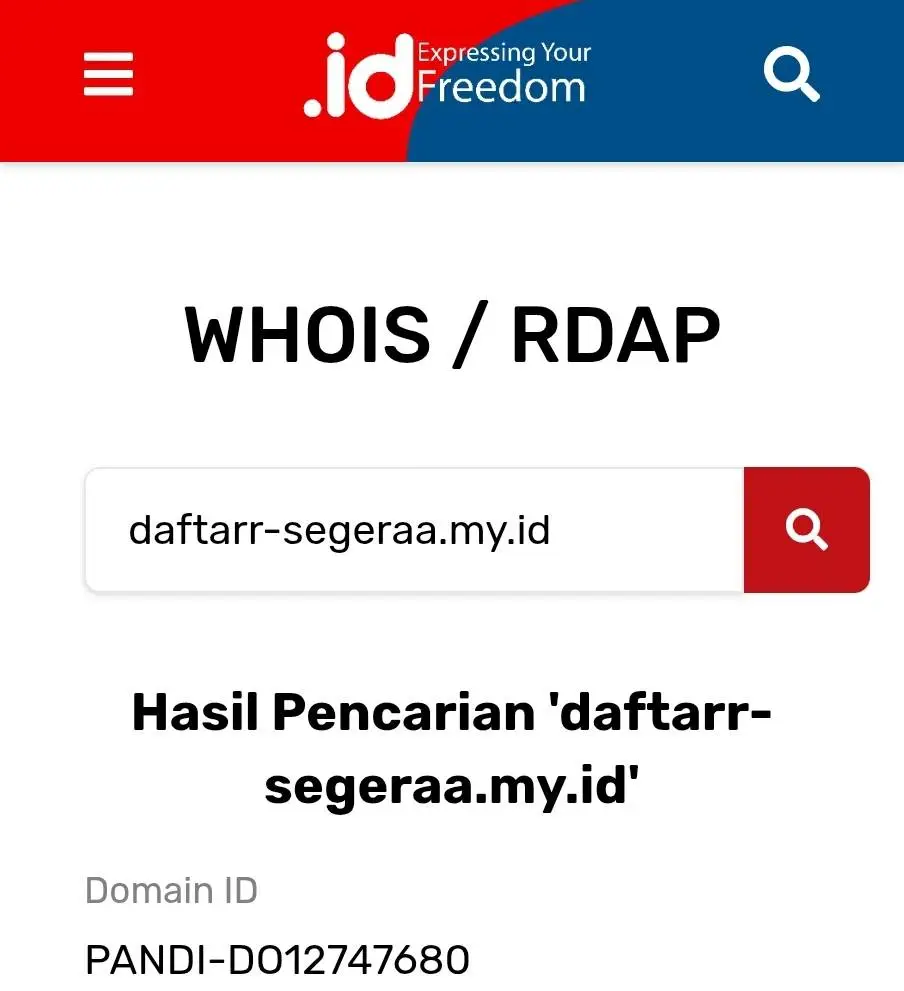Filsafat Kritik Pada Otoritas Politik

Oleh
Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.,C.Med *)
Mengiang di telinga dan rapi dalam lipatan memori, ketika Ibu Mega melarang para kepala daerah dari partainya agar tidak mengikuti retret di Magelang beberapa waktu lalu. Publik terhenyak. Dengan segala keterbatasannya, karakter pemimpin perempuan bernyali ternyata tetap lekat pada diri Ibu Mega. Berani mengatak ‘tidak’ terhadap penguasa. Orang mencemooh. Menuduh mbalelo. Tidak memahami dibalik aksi Ibu Mega dalam perspektif bernegara. Di luar perkiraan, kadang Ibu Mega mengambil langkah ekstrim berseberangan secara terbuka. Menyimpan pesan tentu saja, namun tak semua orang menjadikannya sebagai referensi.
Demikian juga seorang Ibu. Sumarsih namanya. Tetap berdiri mematung setiap Kamis di depan Istana. Berjuang melawan lupa terhadap kekuasaan. Menagih keadilan atas putranya, Bernadinus Realinus Norma Irmawan sebagai korban penembakan Tragedi Semanggi I, 11 – 13 November 1998.
Nasionalisme Ibu Mega membidani rasa sayang kepada NKRI, sedangkan aksi Ibu Sumarsih kepada anaknya bertransformasi menjadi kasih sesama. Sengaja digunakan istilah sayang, bukan cinta, karena cinta dan sayang memiliki perbedaan substanstif. Ketika cinta menguasai rasa maka orang akan memetiknya. Melakukan kalkulasi karena cinta konon butuh pengorbanan. Kalkulasi adalah pretensi pamrih. Namun kasih sayang tidak demikian. Saat kasih sayang datang sebagai anugerah maka orang akan merawatnya hingga batas keabadian. Tidak memetik, apalagi mengambilnya. Dijaga keutuhannya sebagai nilai.
Dua ibu tersebut merupakan simbol ajaran filsafat kritik pada otoritas politik. Penegas bahwa kekuasaan, dalam hal ini bukanlah sumber kebenaran mutlak. Tidak selalu linier dengan gerak hati. Butuh dikoreksi agar tidak mengubur nurani dan mengingkari konstitusi.
Tak kalah pentingnya dengan Ibu Mega dan Sumarsih, terdapat narasi yang menjadi jimat demokrasi sebagai optik kekuasaan, ….‘Power tend to corrupt….’ Demikian nasihat Lord Acton. Guru besar Cambridge University. Maknanya, entitas kuasa dan kekuasaan cenderung korupsi. Kekuasaan dalam bahasa politis adalah otoritas. Hukum, mengistilahkan sebagai wewenang dan kewenangan. Otoritas identik dengan bangunan kelembagaan supra struktural. Pemerintah merupakan lembaga otoritatif. Memiliki otoritas menerapkan aturan. Memberikan kebijakan berdasarkan asas pemerintahan. Mewujudkan amanat konstitusi dengan mendengar aspirasi. Pemerintah daerah dalam skema ketatanegaaraan adalah otoritas normatif. Sementara dalam konteks pelayanan publik disebut otoritas politik.
Nasihat Lord Acton melahirkan inspirasi gerak. Perilaku Ibu Mega menumbuhkan nyali. Kasih sayang Ibu Sumarsih merawat konsistensi. Kekuasaan sebagai otoritas pelayanan publik butuh kontrol. Saran dan masukan serta evaluasi agar tidak melenceng di luar garis batas. Kebutuhan demikian harus disadari, tumbuh dan berkembang serta dirawat dari internal otoritas itu sendiri. Di sinilah urgensi kritik mendapatkan legacy politik. Filsafat kritik memperoleh legitimasi etik. Bahkan pada gilirannya menginspirasi amandemen konstitusi. Filsafat kritik sebagai fakta tak bisa diingkari. Kontributif sebagai penguatan civil society di hadapan otoritas. Filsafat kritik terbukti melahirkan perubahan. Menjebol stagnasi.
Ketika otoritas politik menjalin relasi dialektika maka pemerintah atau pemerintah daerah akan sarat dengan preskripsi. Kaya alternatif solusi. Penuh kreasi membumikan metode. Semua variabel dapat dikelola secara fleksibel. Tersaji berbagai pilihan cerdas sehingga RPJMD berjalan on the track.
Otoritas sebagai bangunan yang tidak pejal kritik merupakan kesadaran internal yang tidak mudah datang seperti membalik telapak tangan. Tidak heran jika secara empiris otoritas di seantero negeri ini dalam hirarkinya anti kritik. Kritik diposisikan sebagai virus. Para tukang kritik dianggap musuh. Narasi kritik dikatakan nyinyir. Jangankan otoritas yang bekerja mengelola kepentingan, keberadaan ilmupun membutuhkan kritik. Sehingga timbul aliran Filsafat Kritik terhadap berbagai dimensi. Baik sejarah, ideologi, seni, hingga lembaga politik seperti pemerintah dan pemerintah daerah.
Tidak semua pemimpin daerah memahami hakikat keberadaan dirinya sebagai representasi kehadiran negara. Dianggapnya, indikator keberhasilan memimpin tidak lain terpenuhi kebutuhan fisik infra struktur dan sejenisnya. Berkurangnya beban hidup masyarakat dengan stimulan fasilitas gratis yang memposisikan masyarakat sebagai pengguna. Tidak heran jika paradikma keberhasilan pembangunan bagi masyarakat identik dengan bantuan. Dilakukan top down dan serta merta.
Padahal makna keberhasilan kepala daerah juga diukur dari sejauh mana yang bersangkutan bersahabat dengan tekanan unjuk rasa sebagai manifestasi daya kritis masyarakat yang dipimpinnya. Seberapa banyak kasus yang bisa diungkap sebagai wujud kesadaran hukum publik dan konsistensi aparatnya. Seberapa berani kepala daerah melakukan reposisi aparatur yang tidak produktif dan membebani dalam rangka reformasi birokrasi. Seberapa konsisten melakukan operasi anti Nepotisme terhadap rekanan di sekitarnya. Di sinilah pentingnya kasanah kognitif otoritas politik untuk mengerti soal filsafat kritik.
Ketika filsafat kritik dipahami sebagai konsekuensi dialektik yang bersifat dogmatis konstitusional maka otoritas politik akan jauh dari prasangka. Bersih dari curiga. Ringan mengimplementasikan langkah. Semua kebijakan bersifat rasional. Setiap pengambilan keputusan jauh dari sikap emosional. Perspektif prioritas pembangunan lebih empatif. Bahkan filsafat kritik bisa membongkar fanatisme. Melalui pemahaman akan filsafat kritik, maka pertimbangan terhadap aturan menjadi lebih penting dari bisikan. Filsafat kritik akan memberikan koreksi selektif kualitatatif. Bisa memilih dan memilah keberadaan individu, antara mereka yang hanya bisa ngomong, tidak terampil momong dan berwatak garong dengan individu profesional menjunjung nalar.
Filsafat kritik harus ditanamkan kepada kepala daerah. Dialirkan untuk para kepala dinas. Dilekatkan pada operator birokrasi agar program kerja daerah juga mempertimbangkan impact. Tidak sebatas menghabiskan anggaran dengan prinsip ‘pokok’e terserap. Hasil terlihat meskipun setelahnya ‘ambruk’. Pemerintah daerah harus membuka kelas filsafat kritik untuk para Camat hingga Kepala Desa agar birokrasi berjalan atas dasar norma. Bukan loyalitas buta. Tidak sensitif dikritik. Tidak gampang anti pati terhadap evaluasi. Tidak menutup pintu saran masukan publik dan peka terhadap kebutuhan daerahnya. Tidak merasa benar sendiri sebagai aparatur politik birokrasi sementara menganggap khalayak adalah pandir dan miskin ilmu.
Paradikma kepemimpinan dan elektabilitas dewasa ini adalah proaktif datang membuka hati dan pikiran untuk mendapatkan kritik. Menerima kritik pada prinsipnya sebagai upaya memanusiakan manusia sebagai wujud kesadaran mendengar karena dirinya sarat dengan keterbatasan. Logikanya, pemimpin dipilih rakyat untuk melayani masyarakat. Membangun maslahat bukan merawat khianat.
Ingat, ketika Salman Rusdi pengarang buku Ayat-Ayat Setan, dilaknat Khomeini dan dinyatakan halal darahnya, dengan rasa percaya diri menjawab pertanyaan wartawan. ‘Aku tidak takut apapun atas ancaman kematian propaganda pemimpin Iran’. Belum tuntas mengutarakan jawaban itu, terdengar letupan bunyi mesin kendaraan seperti senapan di London Street. Sontak bahasa tubuhnya mengindikasikan ketakutan. Ternyata bahasa non verbal tidak selalu mencerminkan apa yang diutarakan. Tidak hanya Salman Rusdi, para kepala daerah dewasa ini juga banyak mengalami patologi Salman Rusdi. Ucapan tidak sesuai pelaksanaan. Di sinilah urgensi filsafat kritik bekerja.
*) Penulis adalah kolumnis, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Ketua Dewan Pakar ICMI Jember, Mediator Berlisensi MA dan Nominator Dosen Favorit Nasional 2024 Versi Hukumonline
Dapatkan Berita Terbaru: Saluran WA
Temukan Berita Terbaru: Google News